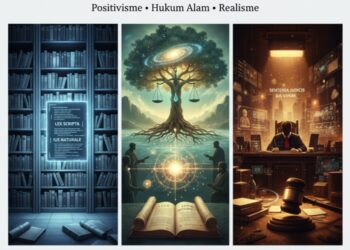Hukum sejak lama dipandang bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, melainkan juga sebagai sarana untuk mengubah perilaku sosial. Pandangan ini dikenal dengan konsep law as a tool of social engineering atau hukum sebagai instrumen rekayasa sosial.
Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Roscoe Pound, seorang ahli hukum asal Amerika Serikat, pada awal abad ke-20. Pound melihat bahwa hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga dapat digunakan secara sadar oleh negara dan masyarakat untuk menciptakan tatanan sosial baru yang dianggap lebih baik.
Dalam konteks Indonesia, peran hukum sebagai rekayasa sosial terlihat jelas sejak era kemerdekaan. Undang-Undang Dasar 1945, berbagai undang-undang organik, serta kebijakan hukum lainnya selalu mengandung unsur transformasi sosial. Misalnya, land reform di era Orde Lama, pembangunan ekonomi berbasis hukum di era Orde Baru, hingga kebijakan reformasi hukum pasca-1998. Dengan kata lain, hukum bukan sekadar refleksi dari kondisi sosial, tetapi juga instrumen untuk mengubah kondisi sosial itu sendiri.
Tulisan ini akan membahas secara mendalam bagaimana hukum diposisikan sebagai instrumen rekayasa sosial, baik secara teoretis maupun praktis. Selain itu, esai ini juga akan mengulas contoh nyata penerapan konsep ini di Indonesia dan berbagai negara lain, serta menelaah tantangan dan kritik yang muncul dalam implementasinya.
Landasan Teoretis: Roscoe Pound dan Social Engineering
Roscoe Pound adalah tokoh utama yang menggagas konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Baginya, hukum harus dilihat sebagai sarana untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Ia membagi kepentingan itu ke dalam tiga kategori utama: kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Menurut Pound, hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyeimbangkan dan mengakomodasi ketiga kepentingan tersebut.
Konsep social engineering yang diperkenalkan Pound menekankan bahwa hukum dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat, misalnya mengurangi konflik, menciptakan kesetaraan, atau mendorong pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, hukum bukanlah sesuatu yang netral, melainkan sarana yang dipakai oleh kekuasaan politik untuk membentuk masyarakat sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.
Dalam literatur hukum modern, pandangan Pound banyak diperdebatkan. Sebagian sarjana menganggap konsep ini terlalu instrumental dan berisiko menempatkan hukum sebagai alat kekuasaan semata. Namun, banyak pula yang menilai bahwa tanpa dimensi rekayasa sosial, hukum hanya akan menjadi kumpulan norma yang kaku dan kehilangan relevansinya dengan dinamika masyarakat.
Hukum sebagai Cerminan dan Pendorong Perubahan Sosial
Perdebatan klasik tentang hubungan hukum dan masyarakat dapat dilihat dari dua pandangan utama. Pertama, hukum dianggap sebagai cerminan masyarakat. Artinya, hukum lahir dari nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Pandangan ini sering dikaitkan dengan teori hukum sosiologis Émile Durkheim atau Eugen Ehrlich. Kedua, hukum dianggap sebagai pendorong perubahan sosial. Pandangan ini menekankan peran negara dan pembuat kebijakan hukum dalam mendorong transformasi sosial.
Kenyataannya, kedua pandangan tersebut tidak bisa dipisahkan. Hukum memang lahir dari realitas sosial, tetapi pada saat yang sama ia juga berperan dalam mengubah realitas itu. Sebagai contoh, hukum pernikahan di Indonesia merefleksikan nilai religius dan budaya bangsa, tetapi juga digunakan untuk mendorong perubahan, seperti pengaturan usia minimal perkawinan guna menekan angka perkawinan anak.
Fungsi Hukum dalam Rekayasa Sosial
Ada beberapa fungsi penting hukum ketika dipandang sebagai instrumen rekayasa sosial:
1. Fungsi Regulatif
Hukum mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan tertentu. Misalnya, undang-undang lalu lintas dibuat untuk menciptakan ketertiban di jalan, tetapi juga untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang sebelumnya tidak disiplin dalam berkendara.
2.Fungsi Redistributif
Hukum digunakan untuk membagi kembali sumber daya secara lebih adil. Contoh klasik adalah Undang-Undang Pokok Agraria 1960 yang bertujuan melakukan reformasi agraria demi keadilan sosial.
3. Fungsi Protektif
Hukum melindungi kelompok rentan dalam masyarakat. Misalnya, hukum ketenagakerjaan yang melindungi hak buruh dari eksploitasi pengusaha.
4. Fungsi Progresif
Hukum mendorong masyarakat untuk meninggalkan praktik lama yang dianggap merugikan. Contoh nyata adalah undang-undang yang melarang diskriminasi atau kekerasan berbasis gender.
5. Fungsi Integratif
Hukum menjadi sarana untuk menyatukan berbagai kepentingan yang berbeda dalam masyarakat plural. Misalnya, hukum nasional di Indonesia harus mampu mengakomodasi keragaman hukum adat dan agama.
Studi Kasus: Rekayasa Sosial Melalui Hukum di Indonesia
1. Reformasi Agraria
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 adalah contoh jelas penggunaan hukum untuk rekayasa sosial. UUPA berusaha menghapus dualisme hukum kolonial dan adat, serta mengatur distribusi tanah yang lebih adil. Walaupun implementasinya menghadapi banyak tantangan, semangat rekayasa sosial dalam UUPA tetap penting dicatat.
2. Kebijakan Pendidikan
Wajib belajar 9 tahun (kemudian 12 tahun) adalah kebijakan hukum yang bertujuan merekayasa pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Dengan adanya aturan ini, negara berusaha menciptakan generasi yang lebih terdidik dan kompetitif.
3. Hukum Lingkungan
Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Cipta Kerja menampilkan dinamika hukum sebagai rekayasa sosial. Di satu sisi, aturan lingkungan berusaha mendorong masyarakat lebih peduli pada kelestarian alam, di sisi lain hukum juga dipakai untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi.
4. Reformasi Demokrasi
Pasca-Reformasi 1998, lahir berbagai undang-undang tentang partai politik, pemilu, hingga kebebasan pers. Semua ini dimaksudkan untuk merekayasa masyarakat Indonesia dari sistem otoriter ke arah sistem demokrasi yang lebih terbuka.
Tantangan dan Kritik terhadap Konsep Hukum sebagai Rekayasa Sosial
Walaupun ideal, penggunaan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial tidak lepas dari kritik. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:
1. Gap antara Hukum dan Realitas Sosial
Banyak hukum yang dibuat tanpa memperhatikan kondisi riil masyarakat, sehingga sulit diimplementasikan. Contohnya, aturan lalu lintas sering diabaikan karena budaya disiplin masyarakat belum terbentuk.
2. Politik Hukum yang Bias Kekuasaan
Karena hukum dibuat oleh pemegang kekuasaan, seringkali ia lebih mencerminkan kepentingan elite daripada kebutuhan masyarakat luas. Hal ini membuat hukum menjadi alat legitimasi, bukan rekayasa sosial yang adil.
3. Pluralisme Hukum
Indonesia memiliki hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama. Rekayasa sosial melalui hukum nasional sering berbenturan dengan norma adat atau agama yang sudah mengakar kuat.
4. Resistensi Sosial
Perubahan sosial yang dipaksakan melalui hukum kadang menimbulkan resistensi. Misalnya, kebijakan pajak karbon atau pelarangan tambang rakyat sering ditolak karena bertentangan dengan kepentingan lokal.
Hukum dan Modernisasi Masyarakat
Dalam perspektif modernisasi, hukum dilihat sebagai sarana untuk mempercepat pembangunan dan menyesuaikan masyarakat dengan tuntutan global. Misalnya, hukum perdagangan internasional mendorong masyarakat untuk mengikuti standar global. Namun, modernisasi hukum juga membawa risiko ketergantungan pada sistem hukum Barat yang belum tentu sesuai dengan nilai lokal.
Hukum Progresif dan Rekayasa Sosial di Indonesia
Prof. Satjipto Rahardjo mengembangkan konsep hukum progresif yang dekat dengan gagasan hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum progresif menekankan bahwa hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya kepastian formal. Dengan demikian, hukum progresif mendorong aparat hukum untuk berani melakukan terobosan demi kemaslahatan masyarakat. Konsep ini sangat relevan bagi Indonesia yang sedang berusaha membangun tatanan sosial yang lebih adil.
Kesimpulan
Hukum sebagai instrumen rekayasa sosial adalah gagasan penting yang menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan kaku, melainkan sarana dinamis untuk membentuk masyarakat. Melalui fungsi regulatif, redistributif, protektif, progresif, dan integratif, hukum dapat mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan seimbang.
Namun, penerapan konsep ini tidak lepas dari tantangan. Hukum yang tidak sesuai dengan realitas sosial atau yang bias kepentingan elite akan sulit berfungsi sebagai rekayasa sosial. Oleh karena itu, pembuat kebijakan hukum perlu memperhatikan aspirasi masyarakat, nilai budaya lokal, dan prinsip keadilan substantif.
Dalam konteks Indonesia, hukum telah digunakan untuk berbagai rekayasa sosial, mulai dari agraria, pendidikan, lingkungan, hingga demokrasi. Walaupun implementasinya sering menghadapi kendala, semangat untuk menjadikan hukum sebagai instrumen perubahan tetap relevan dan perlu diperkuat.
Ke depan, hukum Indonesia perlu dikembangkan tidak hanya sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen transformatif yang menuntun masyarakat menuju keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.